Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan uli al-amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS al-Nisa' [4]: 5).
Dalam bermasyarakat, keberadaan pemimpin mutlak diperlukan. Islam pun secara tegas mewajibkan kebera-daannya. Lebih dari, Islam juga menetap-kan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi pemimpin; serta sistem yang harus dijalankan oleh pemimpin itu.
Kesimpulan itu didasarkan pada banyak dalil. Di antaranya adalah dalam QS al-Nisa ' [4]: 59. Ayat ini memberikan gambaran global kepada kita tentang dua perkara penting dalam kepemimpinan, yakni: kriteria pemimpin dan sistem yang wajib dijalankan pemimpin tersebut.
Wajib Beraqidah Islam
Allah SWT berfirman: Yâ ayyuhâ al-ladzîna âmanû athî'ûLlâh wa athî'û al-Rasûl wa ulî al-amri munkum (hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul [Nya], dan uli al-amri di antara kamu). Seruan ayat ini ditujukan kepada seluruh kaum Mukmin. Mereka diserukan untuk bersikap taat terhadap tiga pihak.
Pertama, taat kepada Allah SWT. Yakni menjalankan perin-tah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sebagaimana dijelaskan banyak mufassir, maksud taat kepada kepada Allah SWT di sini adalah mengikuti al-Quran.
Kedua, taat kepada Ra-sulullah SAW. Sebagai seorang rasul yang diutus untuk mengemban risalah-Nya, Rasulullah SAW wajib ditaati. Bahkan mentaati Rasulullah SAW sama halnya dengan mentaati Zat yang mengutusnya, Allah SWT (lihat QS al-Nisa' [4]: 64, 80).
Kendati mentaati Ra-sulullah SAW paralel dengan mentaati Allah SWT, namun dalam ayat ini kedua-duanya disebutkan. Hal itu menunjukkan perbedaan objek yang ditunjuk. Jika mentaati Allah SWT menun-juk kepada Kitabullah, maka mentaati Rasulullah SAW menun-juk kepada al-Sunnah al-Nabawiyyah. Keduanya, meskipun sama-sama wahyu dari Allah SWT yang wajib ditaati, terdapat perbedaan. Jika al-Quran, lafadznya dari Allah SWT, maka al-Sunnah, lafadznya dari Ra-sulullah SAW sendiri.
Ketiga, taat kepada ulî al-amri. Menurut pendapat jumhur ulama, --sebagaimana dituturkan al-Qurthubi dan Ibnu 'Athiyah-- makna ulî al-amri di sini adalah umarâ' atau khulafâ'. Terhadap mereka, kaum Musim juga diwajibkan untuk mentaatinya. Hanya saja, ketaatan terhadap pemimpin itu dalam koridor ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka wajib ditaati selama tidak melanggar syara'. Apabila terkatagori maksiat, maka tidak boleh ditaati. Rasu-lullah SAW bersabda: Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Azza wa Jalla (HR Ahmad dari Ali ra).
Wajibnya mentaati uli al-amri ini juga menunjukkan hukum wajibnya mewujud-kannya. Sebab, tidak mungkin Allah SWT mewajibkan kaum Muslim untuk taat kepada seseorang yang tidak ada wujud-nya. Sehingga perintah mentaati waliyy al-amri itu bisa juga dipahami perintah agar mewujudkannya. Demikian Syekh Taqiyuddin al-Nabhani dalam Nizhâm al-Hukm.
Kata minkum memberikan batasan bahwa uli al-amri itu harus min al-muslimîn (dari kalangan Muslim). Ini menjadi dalil bahwa khalifah harus seorang Muslim. Kesimpulan itu makin kukuh tatkala dalam al-Quran tidak didapati kata “uli al-amr” kecuali disertai penjelasan bahwa mereka dari kalangan kaum Muslim. Juga firman Allah SWT: Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai (atau mengalahkan) orang-orang beriman (TQS al-Nisa' [4]: 141).
Wajib Menerapkan Syariah
Selanjutnya Allah SWT berfirman: fain tanâza'tum fî syay'[in] faruddûhu ilaLlâh wa al-Rasûl (kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah [al-Quran] dan Rasul [sunnahnya]). Kata tanâzu' menggambarkan adanya perselisihan dan perdebatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Sedangkan kata syay'[in] (sesuatu) meliputi semua urusan, baik urusan al-dîn maupun dunia. Namun ketika dilanjutkan faruddûhu ilaLlâh wa al-Rasûl, maka kalimat itu menjelaskan bahwa sesuatu yang diperselisih-kan itu adalah urusan al-dîn. Demikian penjelasan banyak mufassir, seperti al-Alusi, al-Syaukani, al-Khazin, al-Baghawi, dan lain-lain.
Ditegaskan ayat ini, apabila terjadi perselisihan --baik antara rakyat dengan rakyat atau rakyat dengan penguasa-- maka mereka diperintahkan untuk mengembalikannya kepada Allah dan al-Rasul. Itu artinya, solusi akhir atas setiap perse-lisihan adalah al-Kitab dan al-Sunnah.
Ketentuan ditegaskan dalam frasa berikutnya: in kuntum tu'minûna bil-Lâh wa al-yawmi al-âkhir (jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian). Mengomentari kalimat ini, Ibnu Katsir menyatakan, ”Kalimat tersebut menunjukkan bahwa orang yang tidak meminta keputusan pada perkara yang diperselisihkan kepada al-Quran dan al-Sunnah dan tidak merujuk kepada keduanya, maka dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.”
Ayat ini kemudian diakhiri: Dzâlika khairu wa ahsanu ta'wîl[an] (yang demikian itu lebih utama [bagimu] dan lebih baik akibatnya). Kata Dzâlika menunjuk kepada tindakan mengembalikan kepada al-Kitab dan al-Sunnah. Sementara ahsanu ta'wîl[an] sebagaimana dijelaskan Qatadah berarti ahsanu tsawâb[an] wa khayru âqibat[an] (sebaik-baik pahala dan seutama-utama akibat). Pujian ini kian mengukuhkan wajibnya penerapan syariah.
Kendati singkat, ayat ini telah memberikan gambaran global mengenai kepemim-pinan. Dari aspek pemimpinnya, mereka disyaratkan harus Mus-lim. Sementara sistem yang dijalankan dalam kepemimpinan itu adalah syariah.
Tidak dalam Konteks Demokrasi
Bertolak dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang diperintahkan untuk ditaati dalam ayat ini tidak dalam konteks demokrasi. Dalam demokrasi, kriteria dan syarat pemimpin diserahkan kepada parlemen yang dianggap seba-gai representasi rakyat. Ttidak ada ketentuan baku harus Mus-lim. Bahkan bisa saja parlemen menyetujui larangan Muslim menjadi pemimpin.
Demikian juga sistem yang diterapkan. Semua perundang-undangan harus mendapatkan persetujuan lembaga legislatif. Inilah prinsip dasar dalam demokrasi: Kedaulatan di tangan rakyat. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat harus dipatuhi. Konsekuensinya, rakyatlah yang berhak menentukan sistem, hukum, dan konstitusi yang diterapkan. Tidak peduli apakah semua itu sejalan atau ber-lawanan dengan syariah.
Prinsip dasar demokrasi itu jelas bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini mewajibkan ketaatan mutlak kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Memang uli al-amri juga wajib ditaati. Akan tetapi, ketaatan tersebut harus dalam koridor syariah. Itu artinya, ayat ini menetapkan bahwa kedaulatan di tangan syara'. Ketetapan ini meniscayakan, semua hukum dan undang-undang yang diberlakukan wajib bersumber dari keduanya.
Pertentangan lainnya ada-lah dalam solusi akhir tatkala terjadi perselesihan. Ayat ini menetapkan, setiap perselisihan yang terjadi wajib dikembalikan kepada syariah. Apa pun keputusannya, mereka wajib tunduk terhadapnya.
Sementara dalam demok-rasi, solusi akhir ketika terjadi perselisihan adalah suara ter-banyak. Kata pemutus dalam demokrasi adalah kehendak mayoritas. Ide, aspirasi, atau kebijakan apa pun yang menda-patkan dukungan suara ter-banyak, harus diterima sebagai keputusan terakhir yang ditaati oleh semua pihak. Tidak peduli apakah keputusan tersebut benar atau salah; sejalan atau bertabrakan dengan hukum Allah SWT.

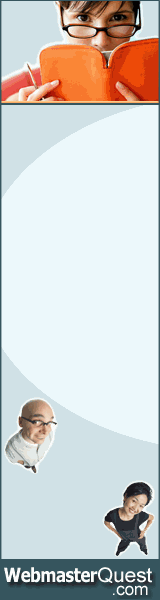





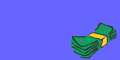

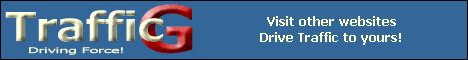

Tidak ada komentar:
Posting Komentar